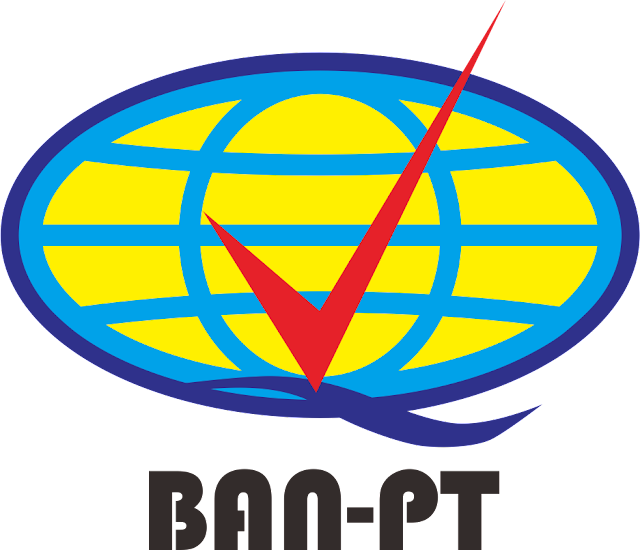Penulis: Dr Askar
Krisis humanitas dalam pendidikan modern semakin menunjukkan gejala yang yang sangat kritis. Di banyak kampus dan sekolah modern kita banyak menyaksikan perilaku siswa yang menggelisahkan banyak pihak, perilaku bulyying, seks bebas, kekerasan dalam lembaga pendidikan semakin menggejala, siswa membantah, melawan dan bahkan memperkarakan gurunya secara hukum, karna ditegur, atau “dipukul” semakin biasa terjadi, uniknya lagi orang tua pun ikut terlibat menekan lembaga pendidikan bahkan melaporkan guru yang melakukan kekerasan kepada anaknya.
Pakar Ruhiologi, Iskandar Nazari bahkan memberikan ungkapan yang sangat menarik. Menurutnya, sekarang ini banyak anak didik yang cerdas secara teknologi, tetapi lemah secara ruhani dan miskin kendali diri. Guru semakin banyak bekerja, tetapi semakin sedikit yang bahagia. Sekolah terus dibangun, tetapi jiwa pendidikan pelan-pelan runtuh dari dalam. Anak-anak kita pintar berhitung, tetapi sulit merasakan; pandai berargumentasi, tetapi kehilangan empati. Guru mengajar dengan disiplin, tetapi sering tanpa kehangatan.
Di balik semua kecanggihan kurikulum dan digitalisasi, pendidikan nasional kita perlahan kehilangan ruhnya.
Fenomena di atas menunjukkan bahwa pendidikan masa kini terjebak dalam paradigma instrumentalis, yang menilai keberhasilan melalui indikator teknis dan hasil terukur. Rasionalitas sistem menggeser dimensi batin, relasi, dan empati dari ruang kelas. Di tengah krisis ini, kurikulum perlu direorientasi agar berpihak kembali pada manusia dan nilai cinta sebagai fondasi praksis pendidikan, yakni dari pendidikan berbasis instrumen ke pendidikan yang berbasis relasi.
Pergeseran dari instrumen menuju relasi menuntut perubahan cara pandang terhadap proses belajar. Guru dan siswa bukan lagi pihak yang berjarak, melainkan dua subjek yang berjumpa dalam kesadaran eksistensial, dan karenanya proses pendidikan hanya menemukan maknanya jika dibangun di atas dasar cinta, bukan atas dominasi.
Cinta di sini bukanlah emosi sensual, tetapi komitmen etis dan kesadaran ontologis untuk pengabdian manusia kepada Tuhan dan penghargaan terhadap kemanusiaan. Erich Fromm memandang cinta sebagai tindakan sadar untuk menghormati eksistensi orang lain. Freire menyebutnya cinta adalah prasyarat dialog menuju kasih sayang dan pembebasan. Lukman Thahir, bahkan menukil lebih dalam bahwa dalam tradisi Islam, cinta berakar pada konsep rahmah—kasih yang memanusiakan dan menuntun manusia menuju pengabdian kepada Tuhan. Kurikulum berbasis cinta karenanya menghidupkan kembali dimensi spiritual dan sosial pendidikan.
Tujuan akhir pendidikan dalam kurikulum berbasis cinta, adalah membantu manusia menjadi dirinya sendiri. Kurikulum yang eksistensial membuka ruang bagi refleksi, kebebasan berpikir, dan tanggung jawab moral. Heidegger menekankan, manusia belajar bukan hanya untuk tahu, tetapi untuk menemukan makna keberadaannya di hadapan semesta, manusia dan Tuhan.
Transformasi kurikulum berbasis cinta menuntut perubahan paradigma: dari kontrol menuju dialog, dari evaluasi menuju perjumpaan. Cinta menjadi fondasi etika dan epistemologi pendidikan—menghubungkan akal dan rasa, ilmu dan kemanusiaan. Dengan cinta, kurikulum tidak lagi menjadi alat pengendali, melainkan ruang tumbuhnya kesadaran dan kebebasan sejati. Sebagaimana Ki Hadjar Dewantara menegaskan, pendidikan sejati adalah menuntun kodrat anak agar menjadi manusia yang merdeka dan bahagia.***