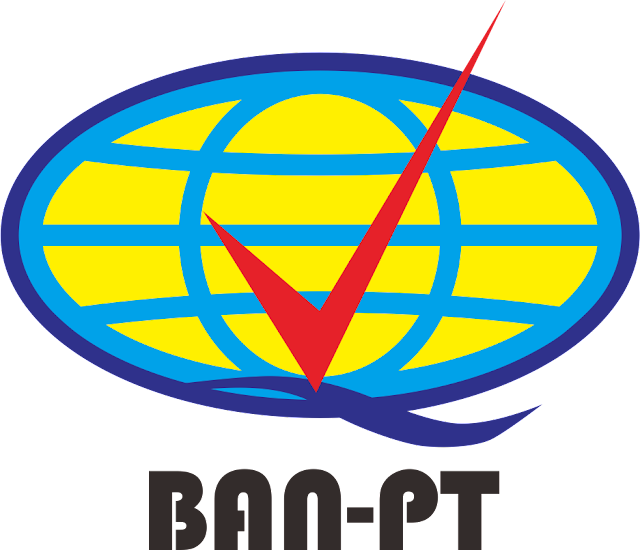Bagian Ketiga dari Seri Jejak-Jejak Safira dan Sang Guru
“Ditulis dengan penuh rasa syukur dan cinta, sebagai persembahan reflektif bagi Prof. Lukman S. Thahir, UIN Datokarama Palu”
Pengantar Reflektif
Cinta dalam pandangan Islam bukan hanya perasaan yang menghubungkan dua manusia, tetapi juga tanda kebesaran Allah yang mengajarkan makna kasih sayang dan ketenangan. Allah menegaskan dalam surah Ar-Rum ayat 21 bahwa di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah diciptakannya pasangan, agar manusia merasakan ketenteraman, dan di antara mereka tumbuh rasa ‘mawaddah’ dan ‘rahmah’.
Mawaddah adalah cinta yang bergejolak — lahir dari naluri, keindahan, dan kebersamaan yang membahagiakan diri. Rahmah adalah cinta yang meneduhkan — lahir dari kasih, pengertian, dan keikhlasan untuk membahagiakan orang lain. Ketika keduanya menyatu, cinta tidak lagi sekadar tentang aku dan engkau, tetapi tentang perjalanan dua jiwa menuju Allah. Dan di situlah makna sejati pernikahan dan kasih sayang menemukan kedamaian: cinta yang menuntun pulang.
Cinta di Bawah Cahaya Rahmah
Sore itu, laut Palu tenang. Langit memantulkan cahaya keemasan, seolah matahari sedang menulis surat cinta kepada bumi sebelum tenggelam. Di beranda rumah kayu yang menghadap laut, duduklah seorang guru tua — Lukman namanya — dan di sampingnya, seorang murid bernama Safira, yang sering datang hanya untuk mendengarkan keheningan yang penuh makna.
Angin sore menyibak lembar-lembar buku di meja. Tiba-tiba, dari kejauhan, mereka melihat sepasang suami istri berjalan berpayung satu. Hujan turun perlahan, lembut seperti doa yang jatuh ke bumi. Sang suami mencondongkan tubuhnya, menutupi istrinya dari hujan, sementara separuh bajunya basah kuyup.
Safira menatap pemandangan itu lama sekali, hingga akhirnya berkata dengan suara lembut, ‘Guru, mengapa lelaki itu rela membasahi dirinya hanya untuk melindungi wanita di sampingnya? Bukankah lebih adil jika keduanya sama-sama berbagi payung?’
Lukman tersenyum, menatap laut yang mulai bergelombang kecil. ‘Karena cinta, Safira, tidak selalu tentang keadilan — kadang ia tentang pengorbanan. Apa yang baru saja kau lihat itu bukan mawaddah, tapi rahmah.’
Safira memiringkan kepala, menatap gurunya dengan keheranan yang manis. ‘Lalu apa bedanya, Guru?’
Lukman menatap jauh ke ufuk senja. ‘Mawaddah, Safira, adalah ketika seseorang berkata dalam hatinya: Aku mencintaimu agar aku bahagia. Ia indah, menggairahkan, penuh warna dan perhatian. Ia membuat seseorang ingin tampil terbaik, berkata lembut, menyentuh, memeluk, dan memastikan dirinya dicintai kembali. Cinta ini tumbuh dari tubuh dan rasa, dan karenanya ia bisa bergetar, bisa pula pudar.’
Safira menunduk, jemarinya menyentuh tetesan hujan yang tersisa di pagar kayu. ‘Lalu rahmah?’ bisiknya.
‘Rahmah,’ lanjut Lukman, ‘adalah cinta yang sudah menembus batas tubuh. Cinta yang berkata: Aku menyayangimu agar engkau bahagia. Ia tidak banyak bicara, tidak mencari sorotan. Ia diam, tapi hangat. Ia tidak menuntut balasan, karena sumbernya bukan dari keinginan, melainkan dari kasih Ilahi yang bersemayam di hati.’
Safira terdiam. Di depan mereka, pasangan itu kini duduk di bawah pohon kelapa. Sang istri tersenyum kecil, menatap suaminya yang masih menggenggam payung patah. Ada keteduhan di sana, seperti doa yang terucap tanpa suara.
‘Jadi,’ kata Lukman lirih, ‘mawaddah adalah nyala, dan rahmah adalah cahaya. Yang satu membakar rindu, yang satu menenangkan jiwa. Dan rumah tangga yang indah adalah rumah yang mampu menjaga keduanya — menyalakan api cinta, tapi tetap sejuk oleh kasih sayang.’
Safira menatap wajah gurunya lama sekali. ‘Guru,’ katanya, ‘kalau begitu, pernikahan itu bukan tentang dua orang yang saling memiliki, tapi dua jiwa yang saling menuntun menuju Tuhan, ya?’
Lukman tersenyum. ‘Benar, Safira. Karena cinta sejati itu bukan saat dua mata saling memandang, tapi saat dua jiwa saling mengingat Allah dalam setiap pandangan.’
Angin laut kembali berhembus, membawa aroma garam dan kesejukan. Senja perlahan berganti malam. Dari kejauhan terdengar azan magrib — mengabarkan bahwa cinta sejati selalu berakhir pada sujud, bukan pada kepemilikan.
Safira menutup matanya, dan dalam hening itu ia mengerti: bahwa mawaddah membuat manusia saling mendekat, tapi rahmah-lah yang membuat mereka bertahan. Dan cinta yang lahir dari keduanya adalah jalan pulang menuju Tuhan.
Renungan Penutup
Cinta yang sejati selalu memiliki arah. Ia tidak berhenti pada keindahan perasaan, tetapi bergerak menuju pengabdian. Dalam setiap relasi manusia, selalu ada dua unsur yang beriringan — gairah untuk memiliki dan keikhlasan untuk memberi. Mawaddah menghidupkan hubungan dengan kehangatan, sedangkan rahmah menenangkannya dengan kasih. Ketika keduanya seimbang, cinta menjelma menjadi ibadah, dan rumah tangga menjadi madrasah bagi jiwa.
Safira memahami bahwa cinta bukan sekadar kata, melainkan perjalanan panjang menuju Allah. Dan pada akhirnya, setiap cinta yang tulus akan menuntun kita pulang — kepada Sang Pencipta Cinta itu sendiri.
Ditulis dengan penuh rasa syukur dan cinta, sebagai persembahan reflektif bagi Prof. Lukman S. Thahir, UIN Datokarama Palu — dalam rangkaian karya Jejak-Jejak Safira dan Sang Guru, menuju peradaban ilmu dan nurani yang berpadu dalam kasih Ilahi. —- Safira***
Bersambung ke Bagian 4…….