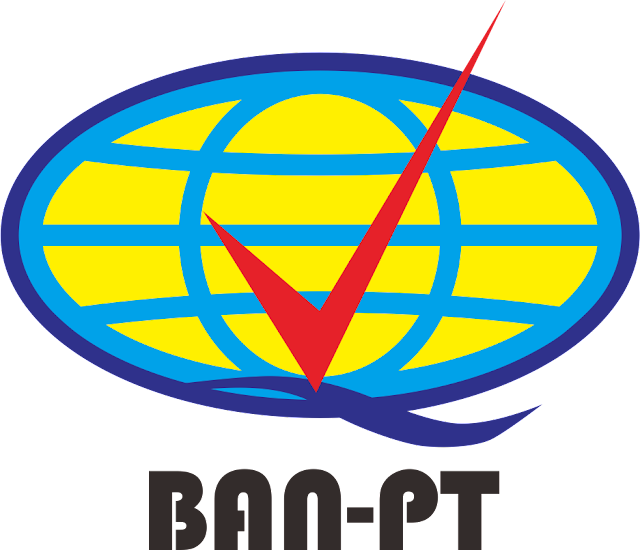Bagian kelima dari Jejak-Jejak Safira dan Sang Guru
“Cinta seorang ibu adalah risalah tanpa huruf, dandoanya menembus langit yang tak pernah salah alamat”— Prof. Lukman.
Pembuka Reflektif
Tidak ada doa yang lebih panjang dari doa seorang ibu, dan tidak ada cinta yang lebih sabar daripada kasihnya.Ia tidak menunggu ucapan terima kasih, tidak menuntut kepulangan, tidak mengukur jarak dengan waktu —ia hanya mencintai dalam diam, dan diamnya adalah bahasa yang dimengerti oleh langit.Bagi anak-anak yang menempuh jalan jauh, doa ibu adalah peta tak terlihat yang menuntun pulang ke cahaya.Dan bagi mereka yang lupa arah, kasih ibu tetap menyalakan lentera —karena cinta sejati tidak pernah mati, hanya berpindah bentuk menjadi rahmat yang mengiringi setiap langkah.Maka berbaktilah ke pada ibu, bukan karena kewajiban, tapi karena cinta.Sebab, pada setiap senyum ibu yang letih, Allah sedang memperlihatkan wajah kasih-Nya yang paling dekat kepada manusia.Perintah berbakti ini, dalam banyak ayat ditegaskan Allah, di antaranya dalam Surah Al-Isrā’ ayat 23–24:
“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua.Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya mencapai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’, dan janganlah engkau membentak mereka, tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah: ‘Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku waktu kecil.’”
Surat untuk Ibu dari Safira
Langit sore itu berwarna abu-abu lembut. Angin dari timur berembus membawa aroma tanah basah setelah hujan. Di balik jendela kayu tua, Safira duduk diam, memandangi selembar kertas kosong di depannya. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam — penyesalan yang sudah lama ia simpan.
Beberapa tahun lalu, ia meninggalkan rumah dengan perasaan getir. Ibunya ingin ia menikah dengan seseorang yang sudah lama dikenal keluarga — lelaki mapan, santun, dan dianggap “aman.” Tapi Safira punya jalan lain. Ia ingin kuliah, menulis, dan berjalan di jalan yang ia yakini sebagai panggilan jiwanya. Pertengkaran kecil di ruang tamu sore itu menjadi api yang membakar jarak antara keduanya.
“Ibu tak pernah melarangmu bermimpi,” kata ibunya waktu itu, “tapi jangan sampai mimpi membuatmu lupa di mana rumahmu.”
“Justru karena aku mencintai rumah ini, aku ingin menemukan diriku dulu, Bu,” jawab Safira, menahan air mata yang nyaris tumpah.Setelah itu, pintu tertutup. Dan hari-hari berikutnya terasa seperti suara detak jam yang memukul kesunyian.
Tiga tahun berlalu. Suatu siang, kabar itu datang. Ibunya wafat — tanpa Safira sempat pulang. Dunia tiba-tiba berhenti berputar. Dalam ruang yang hening, ia menemukan surat ibunya di laci meja, berwarna kecokelatan oleh waktu.
“Safira, jika nanti kau membaca surat ini, mungkin Ibu sudah tak di sisimu. Jangan sesali jalan yang kau pilih. Ibu marah waktu itu bukan karena membencimu, tapi karena takut kehilanganmu. Setiap malam Ibu mendoakanmu agar Tuhan menjagamu lebih lembut dari pelukan Ibu sendiri.”
Air mata menetes di atas huruf-huruf yang mulai pudar. Malam itu, di bawah cahaya lampu redup, Safira menulis surat balasan — surat yang tak pernah akan sampai.
“Bu, aku tidak mencari maafmu, karena aku tahu Ibu sudah memaafkan bahkan sebelum aku salah.Aku hanya ingin bilang, jalan yang kupilih ternyata tetap mengantarkanku pulang — bukan ke rumah yang berdinding, tapi ke doa yang Ibu tinggalkan.”
Beberapa hari kemudian, Safira duduk bersama Sang Guru di tepi senja. Laut memantulkan warna langit seperti hati yang sedang pasrah.
“Guru,” katanya pelan, “aku menulis surat untuk Ibu, tapi aku tahu ia tak akan membacanya.”Sang Guru menatap lembut.
“Safira,” katanya, “suratmu bukan untuk dibaca ibumu, tapi untuk melunakkan hatimu sendiri. Kadang, maaf yang paling sejati bukan yang kita terima, tapi yang kita berani ucapkan kepada diri sendiri.Safira memejamkan mata. Angin laut menyentuh wajahnya, seolah membawa pesan dari tempat jauh. Ia tersenyum samar, lalu berbisik, “Terima kasih, Bu. Aku sudah pulang — lewat doa.” — Safira
Renungan Penutup
Cinta seorang ibu adalah risalah tanpa huruf,dan doa-doanya adalah surat-surat langit yang tak pernah kehilangan alamat.Setiap malam, ia mungkin menatap langit, tidak untuk meminta sesuatu,tetapi untuk memastikan bahwa bintang masih bersinar bagi anak-anaknya di bumi.Dan kelak, ketika sang anak pulang membawa segala pencapaian dan luka,ia akan tahu — bahwa tempat pulang sejati bukanlah rumah, bukan pula waktu,tetapi pelukan doa seorang ibu yang tidak pernah berhenti memanggil namanya dalam sujud. Persembahan dari Safira untuk Sang Guru: Lukman S. Thahir****
Bersambung ke Bagian Enam…..