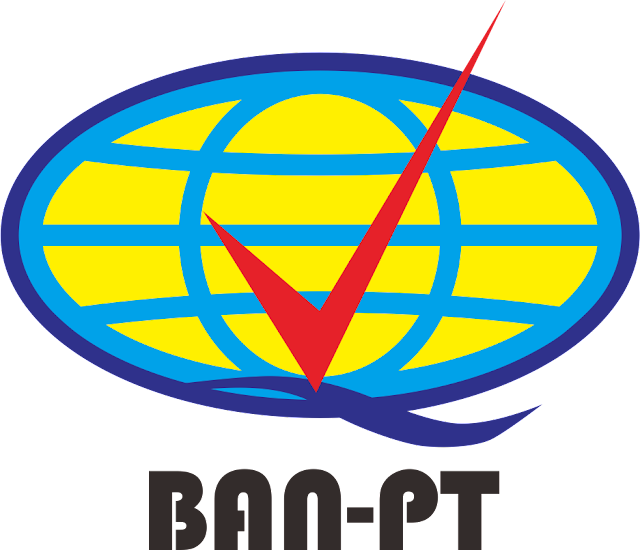Penulis : Mohammad Sadig, M.A., Hum
Soeharto dalam Cermin Sejarah Indonesia
Sejarah Indonesia pasca-kemerdekaan 1945 telah ditandai oleh serangkaian transformasi politik yang mendalam, di mana tokoh-tokoh visioner sekaligus kontroversial memainkan peran sentral dalam membentuk identitas bangsa.
Di antara mereka, Jenderal Soeharto—Presiden Kedua Republik Indonesia—menjadi figur yang paling kompleks dan polarisasi. Memerintah selama 32 tahun, dari 1967 hingga 1998, era Orde Baru di bawah kepemimpinannya bukan hanya periode panjang kekuasaan, tetapi juga fondasi bagi modernisasi Indonesia yang masih terasa dampaknya hingga hari ini, pada 2025.
Warisan Ganda Seorang Pemimpin
Kepergian Soeharto pada 27 Januari 2008, di usia 86 tahun, memicu gelombang refleksi nasional yang terbelah: dari penghormatan sebagai “Bapak Pembangunan” hingga kecaman sebagai simbol otoritarianisme dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Buku Soeharto Memang ‘Hebat’: Menguak Tabir Pro dan Kontra di Balik Kepergiannya karya Wawan H. Purwanto (CMB Press, 2008), misalnya, muncul sebagai respons intelektual yang tepat waktu terhadap dinamika ini, menyajikan analisis seimbang yang menjadi dasar utama seminar ini. Dengan panjang 376 halaman, karya ini tidak sekadar kronologi, melainkan undangan untuk dialog mendalam tentang dualitas kepemimpinan Soeharto—sebuah “kehebatan” yang ironis, di mana pencapaian monumental dibayar dengan luka sosial yang abadi.
Lahirnya Orde Baru: Dari Kekacauan Menuju Stabilitas
Untuk memahami esensi seminar ini, kita perlu menyelami latar belakang historis era Orde Baru. Lahir dari kekacauan akhir Orde Lama di bawah Presiden Soekarno, Orde Baru dimulai secara formal melalui Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret 1966), yang memberikan wewenang luas kepada Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.
Latar belakangnya adalah krisis multidimensional: kegagalan konfrontasi dengan Malaysia (1963–1966), inflasi hiper yang mencapai 650% pada 1965, dan puncaknya adalah peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965 yang dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Komandan Kostrad, memimpin operasi penumpasan yang brutal, menewaskan antara 500.000 hingga 1 juta orang—sebagian besar diduga anggota atau simpatisan PKI—dalam pembantaian massal yang menjadi noda hitam sejarah Indonesia.
Supersemar ini, yang hingga kini kontroversial karena dugaan pemalsuan atau pemaksaan terhadap Soekarno, menandai transisi kekuasaan. Pada 1967, Soeharto secara resmi menjadi Pejabat Presiden, dan pada 1968, ia terpilih secara “demokratis” melalui MPR, meskipun prosesnya didominasi oleh militer. Era Orde Baru, yang berlangsung hingga Reformasi 1998, dirancang sebagai koreksi terhadap “kekacauan” Orde Lama.
Struktur Kekuasaan dan Ideologi Orde Baru
Soeharto menerapkan konsep “demokrasi Pancasila” yang sebenarnya bersifat korporatis, di mana negara mengontrol semua aspek kehidupan melalui dwifungsi ABRI (Angkatan Berdiri Indonesia) dan Golkar sebagai partai dominan. Ciri utamanya adalah stabilitas politik yang ditegakkan dengan tangan besi: Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) menjadi alat represi terhadap oposisi, sementara sensor media dan pembatasan kebebasan berpendapat menjadi norma.
Keberhasilan Ekonomi dan Sosial Orde Baru
Namun, di balik otoritarianisme itu, Orde Baru berhasil membangun fondasi ekonomi yang kokoh. Program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) pertama kali diluncurkan pada 1969, dengan fokus pada stabilisasi moneter melalui bantuan IMF dan Bank Dunia. Hasilnya mencengangkan: pertumbuhan PDB rata-rata 7% per tahun dari 1970-an hingga 1990-an, mengubah Indonesia dari negara miskin menjadi emerging economy.
Swasembada pangan dicapai pada 1984 melalui Revolusi Hijau, di mana produksi beras melonjak dari 12 juta ton menjadi 25 juta ton, mengurangi ketergantungan impor dan kemiskinan dari 60% menjadi 11% populasi. Infrastruktur nasional berkembang pesat: jaringan jalan tol, bandara internasional, dan irigasi sawah yang luas menjadi warisan konkret yang masih dimanfaatkan hari ini. Lebih dari itu, kebijakan sosial Orde Baru menunjukkan visi jangka panjang Soeharto.
Program Keluarga Berencana (KB) yang digulirkan sejak 1970-an berhasil menurunkan angka kelahiran dari 5,6 menjadi 2,3 per wanita pada 1990-an, mencegah ledakan demografis dan mendukung pembangunan manusia.
Pendidikan dasar ditingkatkan melalui Inpres SD (Instruksi Presiden Sekolah Dasar) 1973, yang membangun ribuan sekolah di pelosok, meningkatkan tingkat melek huruf dari 64% menjadi 90%.
Di bidang kesehatan, vaksinasi massal dan posyandu mengurangi angka kematian bayi secara signifikan. Stabilitas politik ini juga meredam konflik etnis dan agama yang meletus di era Soekarno, seperti pemberontakan DI/TII atau PRRI/Permesta, meskipun dengan biaya penindasan minoritas.
Pengamat seperti Daniel S. Lev dalam studinya tentang Orde Baru menyebut periode ini sebagai “keajaiban Asia” bagi Indonesia, di mana negara korporatis berhasil mengintegrasikan ekonomi pasar bebas dengan kontrol negara yang ketat, menarik investasi asing mencapai miliaran dolar dari Jepang dan Amerika Serikat.
“Keajaiban Asia” dan Citra Internasional Indonesia
Dampak positif ini tidak terbantahkan: Indonesia bergabung dengan ASEAN pada 1967, menjadi anggota G-77, dan bahkan diakui sebagai “Bintang Asia” oleh media internasional pada 1980-an.
Namun, “kehebatan” Soeharto tidak lepas dari bayang-bayang kegelapan yang kian pekat seiring berjalannya waktu. Di sisi negatif, rezim Orde Baru menjadi sinonim dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)—istilah yang dipopulerkan oleh mahasiswa selama Reformasi 1998.
Keluarga Soeharto, termasuk istrinya Tien Soeharto dan anak-anak seperti Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) serta Hutomo Mandala Putra (Tommy), menguasai monopoli bisnis: dari tol Trans-Jakarta hingga impor gula dan semen, menghasilkan kekayaan pribadi mencapai US$15–35 miliar menurut perkiraan Time Magazine.
Transparency International menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup di Asia Tenggara pada akhir 1990-an, dengan kerugian negara triliunan rupiah. Lebih tragis lagi adalah catatan pelanggaran HAM yang sistematis.
Sisi Gelap Kekuasaan: Represi dan Pelanggaran HAM
Pembantaian pasca-G30S 1965 bukan hanya pembuka, tapi pola yang berulang: invasi Timor Timur 1975 menewaskan 200.000 jiwa, termasuk pembantaian Santa Cruz 1991; kerusuhan Tanjung Priok 1984 yang menewaskan puluhan demonstran Islam; dan puncaknya kerusuhan Mei 1998 yang menewaskan 1.200 orang, mayoritas etnis Tionghoa, disertai pemerkosaan massal yang tak tertangani.
Otoritarianisme ini juga membungkam suara: pemilu diatur agar Golkar menang 70–80%, media seperti Tempo ditutup pada 1994, dan ribuan aktivis seperti Marsinah (buruh yang dibunuh 1993) menjadi korban hilang paksa. Kritik ini semakin relevan ketika kita melihat kejatuhan Orde Baru.
Kejatuhan Sang Penguasa
Krisis moneter Asia 1997–1998 memperburuk ketimpangan: rupiah anjlok dari Rp2.400 menjadi Rp17.000 per dolar AS, memicu demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan yang memaksa Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Transisi ke Reformasi membuka kotak Pandora: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk, tapi upaya pengadilan
Soeharto atas KKN gagal karena kesehatannya memburuk. Bahkan saat meninggal pada 2008, ia masih berstatus terdakwa di pengadilan Tipikor, meskipun kasusnya dicabut atas permohonan keluarga. Kematian Soeharto di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, setelah 23 hari perawatan intensif akibat gagal jantung dan infeksi, memicu reaksi publik yang mencerminkan polarisasi warisannya.
Wafatnya Soeharto: Antara Duka dan Kontroversi
Pada 27 Januari 2008, berita wafatnya menyebar cepat: kompleks Dalem Kalitan di Solo dipadati ribuan pelayat, termasuk keluarga dan tokoh seperti Megawati Soekarnoputri, yang menyatakan duka cita nasional.
Doa massal di masjid-masjid dan gereja menunjukkan simpati luas; bahkan di desa-desa Jawa Tengah, warga menggelar selamatan tradisional, mengenang Soeharto sebagai “pak harto” yang sederhana—seorang petani yang bersepeda ke kantor.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato nasional, menyebutnya “pemimpin besar” yang membawa kemajuan, dan mengumumkan hari libur nasional untuk pemakamannya di TPU Giri Jati, Jakarta, pada 29 Januari—upacara kenegaraan yang dihadiri 500.000 orang.
Media seperti Kompas dan Tempo melaporkan suasana haru, dengan headline “Pak Harto Wafat dengan Tenang” dari tim dokter kepresidenan. Namun, reaksi ini jauh dari seragam.
Aktivis HAM seperti Yap Thiam Hien dari YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) mengecam pemberitaan media sebagai “tidak proporsional,” menuntut evaluasi atas pelanggaran HAM daripada glorifikasi.
Demonstrasi kecil di depan RSCM oleh kelompok seperti KontraS menuntut pengadilan penuh, dengan spanduk “Soeharto Bukan Pahlawan.” Majalah Tempo edisi Februari 2008 berjudul “Selesai Sudah,” mengkritik upaya pemerintah memberi predikat pahlawan nasional—yang akhirnya gagal—sebagai gegabah.
Di kalangan etnis Tionghoa, trauma Mei 1998 membuat banyak yang diam, sementara di Timor Leste, peringatan diadakan untuk korban invasi. Reaksi internasional pun terbelah: The New York Times memuji pencapaian ekonomi tapi menyoroti “rezim diktator,” sementara mantan Sekjen PBB Kofi Annan menyatakan penghormatan pribadi.
Secara keseluruhan, kematian ini menjadi cermin masyarakat pasca-Reformasi: 60% responden survei LIPI 2008 melihat Soeharto positif untuk pembangunan, tapi 70% menolak pengampunan atas HAM. Di sinilah buku Wawan H. Purwanto masuk sebagai jembatan.
Buku Wawan H. Purwanto: Menjembatani Dua Sisi Sejarah
Sebagai jurnalis dan pengamat intelijen yang dikenal dengan karya tentang terorisme, Purwanto menulis buku ini sebagai refleksi pasca-kematian, mengumpulkan wawancara dengan 50 narasumber dari berbagai spektrum: mantan menteri seperti Widjojo Nitisastro (pro-pembangunan), aktivis seperti Amien Rais (kritikus), hingga korban seperti keluarga korban 1965.
Strukturnya tematik: bagian awal merekonstruksi hari-hari terakhir Soeharto, bagian tengah mengurai pro (ekonomi, stabilitas) dan kontra (KKN, represi), serta penutup merefleksikan warisan untuk demokrasi.
Purwanto menggunakan istilah “hebat” secara ironis, menggemakan pidato Soeharto sendiri, untuk menekankan bahwa evaluasi harus holistik—bukan hitam-putih. Buku ini, yang tersedia di perpustakaan nasional seperti Perpusnas, menjadi rujukan akademis karena netralitasnya, meskipun edisinya langka kini.
Relevansi Refleksi Soeharto di Tahun 2025
Seminar Soeharto Memang ‘Hebat’: Refleksi Warisan Orde Baru pada 2025 ini relevan karena Indonesia masih bergulat dengan bayang Orde Baru. Krisis demokrasi kontemporer—seperti polarisasi politik, korupsi endemik (Indeks Persepsi Korupsi 2024 masih 34/100), dan tuntutan rekonsiliasi HAM (UU No. 20/2022)—menggemakan masa lalu.
Di era digital, diskusi sejarah sering terdistorsi oleh media sosial, membuat ruang dialog akademis seperti ini krusial. Dengan basis buku Purwanto, seminar ini bertujuan membuka wacana inklusif, melibatkan generasi muda yang lahir pasca-1998, untuk belajar dari dualitas Soeharto: bagaimana “kehebatan” membangun tapi juga merusak. Ini selaras dengan semangat Pancasila, yang menekankan musyawarah mufakat dan keadilan sosial, guna membangun Indonesia yang lebih matang.***
Tentang Penulis: Mohammad Sadig, M.A., Hum merupakan Akademisi UIN Datokarama Palu / Pemerhati Gerakan Mahasiswa