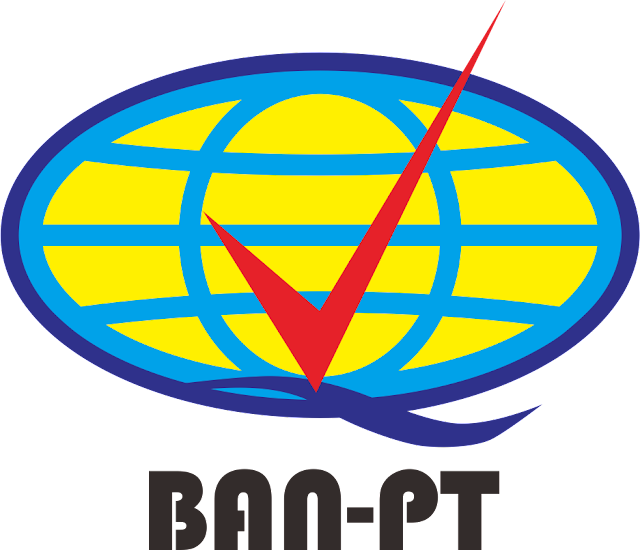Mungkin di antara kita sudah masyhur dengan kisah tawadhu’nya Imam Syafi’. Ketika berkunjung ke masjid Imam Abu Hanifah di Irak dan diminta mengimami salat subuh beliau berkata : Saya tidak qunut, karena saya tahu beliau (Imam Abu Hanifah) berbeda pandangan dengan saya dalam masalah ini.” Imam Syafi’ bersikap demikian, padahal Imam Abu Hanifah saat itu telah wafat, tetapi karena kuburan beliau berada dekat masjid, beliau pun bersikap setakrim itu terhadap imam mazhab, yg juga gurunya.
Dalam istilah orang Bugis, apa yang dilakukan oleh Imam Syafi’ itu adalah ma’tabe’-tabe’. Oleh karena itu, seorang ustaz atau seorang ahli agama yang bijak, ia akan mattabe’-tabe’ ketika mengunjungi suatu majelis, masjid, atau daerah di mana ia tahu pemikiran ulama siapa yang memasyarakat di sana.
Cerita dari seorang sahabat kami, bahwa Gurutta Haritsah (Pendiri Pesantren An-Nahdah Makassar) tidak pernah mau menselonjorkan kakinya jika beliau menghadap ke arah Sengkang. Meski misalnya beliau sedang berada di daerah yang sangat jauh dari Sengkang, karena tingginya penghormatan terhadap guru beliau Anregurutta As’ad (seorang ulama besar di Sengkang), beliau bersikap seperti itu padahal levelnya sudah “gurutta”.
Inilah spirit akhlak ulama yang pelan-pelan lenyap dari generasi kita. Suatu kesyukuran di satu sisi, menyaksikan fenomena anak-anak muda, yang bukan berlatar pendidikan pesantren, memutuskan untuk aktif di kajian-kajian agama. Berkat internet, bahkan tanpa susah payah menempuh jarak ke suatu majelis atau membuka kitab-kitab, anak-anak muda ini dapat memperluas wawasan keislaman mereka lewat media online ulama atau ustaz.
Namun, di sisi lain, ada hal yang juga mengkhawatirkan. Anak-anak muda ini tak sedikit di antaranya yang gemar menghardik dan mencaci ulama atau ustaz yang berbeda pandangan. Ada pula yang sengaja melayangkan pertanyaan provokatif ke seorang ustaz yang acaranya disiarkan secara live, dengan tujuan untuk mengadu domba antar ustaz atau ulama. Pada tingkatan paling ekstrim, mudah sekali mereka mencap “sesat” ulama selevel mujtahid, imam mazhab atau mufti. Maka jangankan mendapatkan keberkahan ilmu, tapi jatuhnya malah dijauhi ilmu.
Saya pribadi, ketika menemukan pendapat-pendapat seorang ahli agama (ulama) yang sekontroversial apapun, saya memilih untuk sekedar menyimpannya sebagai sebuah informasi baru. Di hadapan ulama, saya memposisikan diri sebagai murid, seorang awam, di mana bukan maqamnya seorang ulama disalahkan atau dikritik oleh orang yg bukan ulama.
Alhamdulillah, saya tidak sekalipun pernah berani menyesatkan para ulama atau para ahli agama yang berbeda pandangan, bahkan terpikir untuk menyalahkan pun tidak. Di majelis-majelis masyarakat awam, sebisa mungkin saya tidak akan menyampaikan ketidaksetujuan saya terhadap pandangan ulama untuk menghindari fitnah terhadap mereka dan perpecahan umat.
Ketika membaca kitab Ad-Dur Al-Mantsurnya Imam As-Suyuti tentang tafsir beliau terhadap surah Yusuf, ada riwayat bias dan penjelasan beliau yang saya kritisi, tapi itu tidak menghentikan saya untuk mempelajari karya-karyanya Imam as-Suyuti. Begitu pula ketika saya membaca pendapatnya Imam Abu Hanifah tentang penerapan satu kaidah fikih dalam masalah salat, karena itu berbeda dengan yang selama ini saya ketahui, saya tidak menyalahkan pendapat beliau. Saya berpikir: ow ya, mungkin pendapat ini bisa dipakai dalam kondisi lain. Saya membaca buku Prof Quraish tentang jilbab, meski ada yang tidak sejalan dengan pandangan saya, tapi buku tafsir beliau Al Misbah senantiasa menjadi top list rujukan saya dalam mengkaji tafsir.
Mengapa para ulama ilmunya sangat luas, bukan hanya karena ketekunan mereka, tetapi juga karena hati mereka yang bersih dalam menuntut ilmu. Mereka sanggup menghabiskan waktu sampai usia sepuh untuk berguru, menempuh jarak jauh untuk berpindah dari guru ke guru, menulis buku berjilid-jilid karena kedekatan mereka kepada Allah, Sang Pemberi Ilmu. Ilmu yang mereka punyai, membuat mereka semakin bertakwa, semakin tawadhu’ dan semakin bijak.
Jika kita membaca perdebatan para ulama salaf/klasik, ketika berbeda dalam satu masalah fikih misalnya, yang mereka kedepankan adalah berbagi ilmu atau rasionalitas, sehingga kita yang membacanya pun terkagum-kagum, tidak emosi, tetapi justru dari perdebatan itu banyak sekali ilmu yang dijelaskan. Inilah yang dinamakan dengan rahmat sebagaimana adagium ikhtilaafu ummati rahmah.
Penulis: Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.