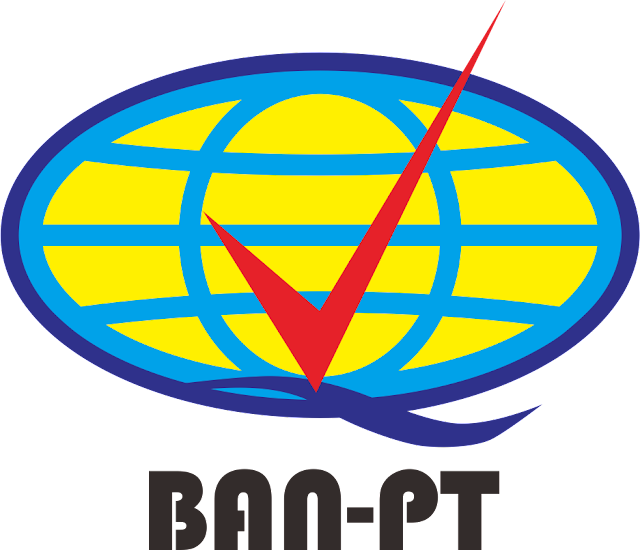Antara Kearifan Lokal, Hak Ibadah, dan Etika Kebersamaan
Oleh: SM Syams
Gema sahur sebagai tradisi dan refleksi ruang majemuk
Pukul tiga dini hari, ketika langit masih menyimpan sisa gelap dan sebagian manusia masih terlelap dalam sunyi, terdengar seruan yang menggema dari corong masjid. “Sahur… sahur… sahur…” Suara itu bukan sekadar bunyi, melainkan tanda. Ia adalah panggilan untuk menyiapkan diri, menyambut fajar dengan niat menahan lapar dan dahaga. Di banyak kampung dan kota, tradisi ini telah menjadi denyut kultural yang diwariskan lintas generasi.
Namun di tengah gema itu, terselip pertanyaan yang tidak sederhana. Bagaimana jika ruang yang sama dihuni oleh mereka yang tidak berpuasa. Bagaimana jika suara yang dimaksudkan sebagai panggilan ibadah dan mereka yang menggemakan menganggap dirinya berpahala, justru dirasakan sebagai ketidaknyamanan orang lain. Di titik inilah, tradisi bertemu dengan memajemukan. Kearifan lokal berhadapan dengan etika sosial yang lebih luas.
Dimensi sosial sahur sebagai praktik kolektif
Dalam masyarakat mayoritas Muslim, tradisi membangunkan sahur memiliki makna yang dalam. Ia tidak semata teknis, tetapi simbolik. Ia menandai solidaritas (ukhuwah), menghidupkan suasana Ramadan, dan menguatkan rasa kebersamaan. Sejak dahulu, cara membangunkan sahur dilakukan dengan kentongan, tabuhan beduk, atau keliling kampung. Kini, teknologi pengeras suara menggantikannya, dan bergema melalui Toa Toa (pengeras suara) Masjid. Perubahan alat tidak sama sekali mengubah niatnya.
Secara sosiologis, ini adalah bentuk praktik kolektif (collective practice) yang membangun identitas komunal. Ia membentuk ruang spiritual bersama, di mana agama hadir bukan hanya di dalam masjid, tetapi juga di ruang publik. Tradisi ini, dalam konteks tertentu, dapat disebut sebagai kearifan lokal karena tumbuh dari kebutuhan masyarakat dan diterima sebagai kebiasaan bersama.
Namun realitas sosial terus bergerak. Di sejumlah wilayah yang lebih majemuk, sensitivitas sosial
menjadi faktor penting. Apa yang wajar di satu tempat, belum tentu diterima dengan cara yang
sama di tempat lain. Konteks menjadi kata kuncinya.
Hak beribadah dan hak atas ketenangan
Indonesia berdiri di atas prinsip kemajemukan, yaitu prinsip kebebasan beragama sekaligus penghormatan terhadap ketertiban bersama. Di dalam satu wilayah, bisa hidup berdampingan
Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan keyakinan lainnya. Dalam kondisi seperti itu, hak
untuk beribadah tidak boleh berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan hak orang lain untuk hidup
tenang secara bersama-sama.
Di sinilah kita perlu menengok kerangka hukum dan etika bersama. Undang-Undang Dasar 1945
menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Namun, pada saat yang bersamaan, kebebasan itu
berada dalam bingkai ketertiban umum dan penghormatan terhadap hak orang lain. Prinsip ini
dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang
menegaskan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari gangguan.
Dalam konteks teknis penggunaan pengeras suara berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama
Nomor 05 Tahun 2022 memberikan pedoman agar penggunaan pengeras suara masjid dilakukan
secara proporsional dan mempertimbangkan kondisi lingkungan. Ini bukan untuk membatasi
ibadah, melainkan untuk menata harmoni.
Karena itu, jika dalam situasi tertentu ada warga yang merasa terganggu dan menyampaikan
keberatan secara santun, hal itu tidak otomatis dapat dimaknai sebagai sikap antiagama. Ia bisa saja merupakan ekspresi hak sebagai warga dalam ruang hidup bersama. Sebaliknya, umat beragama lainpun berhak menjalankan syiar dan tradisinya selama tetap dalam koridor kepatutan sosial. Maka disinilah keseimbangan diuji.
Antara sensitifitas dan kedewasaan sosial
Di ruang publik yang majemuk, yang dibutuhkan bukanlah dominasi, tetapi kedewasaan. Mayoritas tidak otomatis berarti bebas tanpa batas. Sebaliknya, minoritas pun tidak serta merta harus merasa tertekan. Keduanya memerlukan dialog.
Dalam perspektif Islam sendiri, ajaran tentang adab (etika) sangat kuat. Rasulullah mengajarkan agar tidak menyakiti tetangga, tidak mengganggu kenyamanan orang lain, bahkan dalam hal ibadah sekalipun. Spirit agama tidak pernah mengajarkan untuk menegaskan identitas dengan cara yang melukai.
Jika suara sahur dimaksudkan untuk kebaikan, maka cara menyampaikannya pun seyogianya mencerminkan kebaikan. Volume yang terlalu keras, durasi yang panjang, atau repetisi berlebihan
bisa mengubah niat baik menjadi sumber ketegangan sosial atau paling tidak rasa ketentraman dan kenyamanan bagi mereka yang tidak berkepentingan akan hal itu, menjadi terganggu.
Di sinilah kritik struktural yang santun perlu diajukan. Bukan pada niat ibadahnya, tetapi pada tatakelolanya. Pengurus masjid, tokoh agama, dan pemerintah setempat perlu membaca ulang realitassosial. Apakah lingkungan tersebut homogen atau majemuk. Apakah sudah ada musyawarah warga. Apakah volume sudah diukur secara wajar.
Mencari titik temu dalam kebijakan lokal
Setiap wilayah memiliki karakter berbeda. Di kampung yang seluruhnya Muslim, gema sahur mungkin diterima sebagai kebiasaan kolektif. Namun di kompleks perumahan majemuk, pendekatan yang sama bisa memunculkan resistensi.
Maka yang diperlukan bukan pelarangan, melainkan penyesuaian. Secara konseptual, ruang publik harus dikelola dengan prinsip inklusivitas (keterbukaan terhadap semua). Secara praktis, bisa ditempuh langkah seperti membatasi durasi, menurunkan volume, atau mengalihkan pengumuman sahur pada metode yang lebih personal, misalnya melalui grup komunikasi warga.
Dialog warga menjadi kunci. Forum RT, RW, atau musyawarah kampung dapat menjadi ruang
menyepakati standar bersama. Ketika keputusan lahir dari kesepahaman, potensi konflik akan jauh berkurang.
Spirit Ramadan sebagai momentum refleksi
Ramadan pada hakikatnya adalah bulan pengendalian diri. Ia melatih menahan lapar, menahan
amarah, dan menahan ego. Jika demikian, maka Ramadan juga seharusnya menjadi momentum
untuk menahan sikap merasa paling benar.
Gema sahur adalah panggilan untuk bangun sebelum fajar. Namun mungkin ia juga menjadi
panggilan untuk membangunkan kesadaran kolektif tentang pentingnya menghargai perbedaan.
Ibadah yang baik bukan hanya yang sah secara ritual, tetapi juga yang menghadirkan ketenteraman sosial.
Kita hidup di negeri yang dibangun atas kesepakatan kebangsaan. Agama hadir sebagai sumber
nilai dan rahmat, bukan sebagai sumber ketegangan. Maka keberatan warga selain muslim atas
kebisingan bukanlah ancaman terhadap Islam, melainkan pengingat agar praktik keagamaan tetap dalam koridor kebajikan sosial.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan soal boleh atau tidak boleh semata. Ia adalah soal kebijaksanaan. Apakah kita mampu menempatkan tradisi dalam kerangka kemajemukan. Apakah kita mampu mengelola semangat ibadah tanpa mengabaikan hak sesama.
Ramadan mengajarkan bahwa yang paling mulia bukan yang paling keras suaranya, tetapi yang
paling dalam ketakwaannya. Dan takwa itu selalu berwujud pada sikap adil, empatik, dan penuh
pertimbangan terhadap orang lain.
“Ibadah yang luhur bukan hanya yang menggema ke langit, tetapi yang menenangkan bumi
tempat kita berpijak. Sebab di situlah iman diuji, bukan pada kerasnya suara, melainkan pada
lembutnya sikap.”
Tentang Penulis: SM Syams Merupakan Akademisi dan Pemerhati Refleksi Sosial Kemasyarakatan Palu