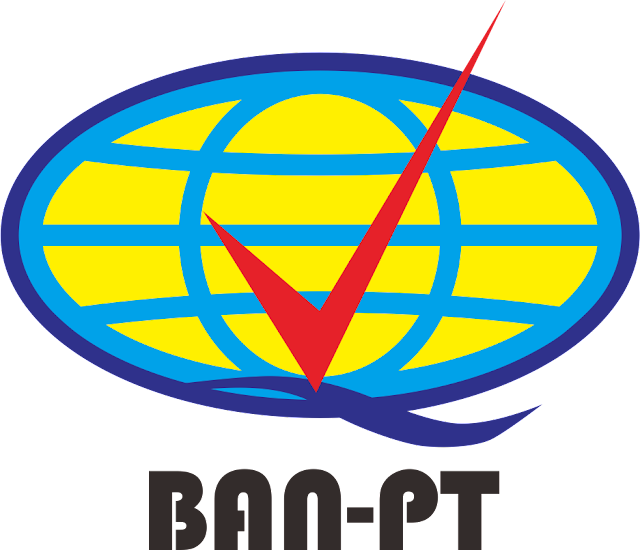Penulis: Prof. Nurdin, M.Com., Ph.D.
Dalam era digital, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah bertransformasi menjadi “penguasa baru pengetahuan” karena kemampuannya mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi dalam skala yang jauh melampaui kemampuan manusia.
AI tidak hanya berperan sebagai alat bantu teknologi, tetapi juga sebagai aktor epistemik—entitas yang mampu membentuk, menyeleksi, dan mengarahkan proses produksi pengetahuan. Sebagai penguasa baru dalam produksi dan distribusi pengetahuan, AI telah memainkan peran sebagai mesin produksi pengetahuan baru dengan cara belajar dari pengetahuan yang disebarkan oleh manusia melalui Internet.
AI mampu mengolah data besar (big data) menjadi informasi dan pengetahuan baru melalui proses pembelajaran mesin (machine learning) dan analisis prediktif. Sistem seperti ChatGPT, Google DeepMind, atau IBM Watson dapat menyintesis jutaan sumber informasi, menemukan pola tersembunyi, dan menghasilkan wawasan yang sebelumnya tidak terlihat oleh peneliti manusia. Dengan demikian, AI menjadi “produsen” pengetahuan baru yang memperluas batas epistemologi manusia.
Dalam ekosistem digital, AI berperan sebagai kurator informasi, menentukan apa yang relevan, penting, atau populer berdasarkan algoritma. Mesin pencari, media sosial, dan platform pembelajaran menggunakan algoritma AI untuk menyaring dan memprioritaskan konten yang ditampilkan kepada pengguna.
Akibatnya, AI memiliki kekuasaan besar dalam mengatur arus pengetahuan—menentukan apa yang diketahui dan apa yang terlupakan. Dulu, otoritas pengetahuan berada di tangan lembaga seperti universitas, perpustakaan, atau guru. Kini, AI menggantikan sebagian peran tersebut melalui sistem rekomendasi, tutor virtual, dan asisten penelitian otomatis.
Banyak individu lebih percaya pada hasil yang dihasilkan oleh algoritma dibandingkan otoritas manusia, menandakan pergeseran dari “otoritas manusiawi” menuju “otoritas algoritmik”.
Namun demikian, kekuasaan AI atas pengetahuan menimbulkan persoalan serius. Pertama, bias algoritmik dapat membentuk pengetahuan yang tidak netral. Kedua, ketergantungan manusia pada AI berpotensi melemahkan kemampuan berpikir kritis dan otonomi intelektual.
Ketiga, monopoli data oleh korporasi besar menjadikan distribusi pengetahuan semakin timpang dan tidak merata. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijaksanaan setiap individu dalam penggunaan AI sebagai sumber pengetahuan terutama pengetahuan terkait agama dan moral. Selanjutnya, meskipun AI tampak sebagai penguasa baru, idealnya ia harus menjadi mitra kolaboratif manusia dalam membangun pengetahuan yang inklusif, etis, dan humanis. Manusia tetap memegang peran dalam memberikan arah moral, konteks budaya, dan nilai kemanusiaan yang tidak dapat direplikasi oleh algoritma.
AI kini bukan sekadar alat bantu, melainkan entitas epistemik yang membentuk cara manusia memahami dunia. Sebagai penguasa baru pengetahuan, AI membawa peluang luar biasa untuk kemajuan, tetapi juga menuntut kebijaksanaan agar kekuasaan atas pengetahuan tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan.
Dengan demikian penguasa pengetahuan tradisional seperti guru, ustaz, sekolah, dan madrasah tidak terpinggirkan karena mereka adalah sumber pengetahuan yang bukan hanya mampu memproduksi dan mentransfer pengetahuan tetapi juga memberi nilai dan moral terhadap pengetahuan tersebut.***
Tentang Penulis: Prof. Nurdin, M.Com., Ph.D. merupakan salah seorang Guru Besar yang dimiliki oleh UIN Datokarama. Saat beliau menjabat sebagai Direktur Pascasarjana