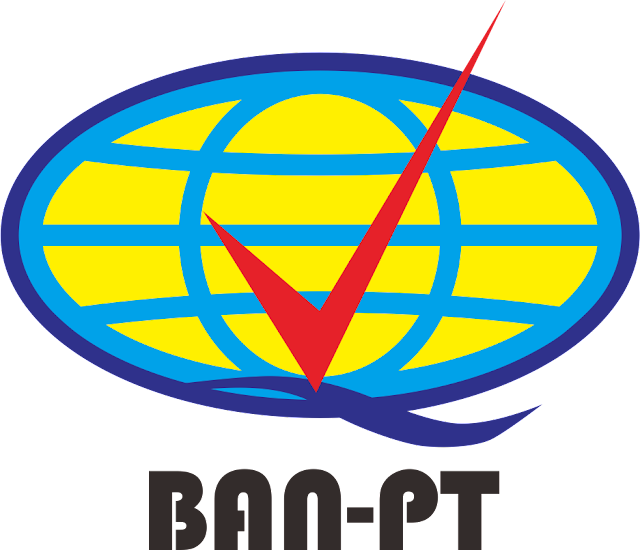Pagi yang Tergesa dari Gajah Mada, Lalove sampai Muh. Yamin
Oleh: SM Syams
Pagi yang Tenang, Manusia yang Tak Sabar
Pagi di Palu selalu datang dengan ketenangan yang khas. Matahari terbit dari balik bukit Pompangeo atau dikenal warga kota Palu sebagai Bulumasomba yang perlahan membuka Teluk Palu, menghadirkan cahaya lembut yang seolah mengajak manusia memulai hari dengan kesadaran. Alam bekerja dengan sabar, tanpa tergesa, seakan memberi isyarat bahwa setiap awal sepatutnya dijalani dengan niat yang baik dan langkah yang tertib.
Namun ketenangan itu kerap berhenti di batas lanskap. Begitu roda kendaraan mulai bergerak, suasana berubah. Jalan-jalan utama ”dari Gajah Mada, Lalove, hingga Muhammad Yamin” menjadi ruang yang penuh dorongan untuk saling mendahului. Gas ditarik lebih dalam, klakson menjadi penanda keberadaan, dan waktu terasa seperti sesuatu yang harus ditaklukkan.
Pada jam enam hingga delapan pagi, Palu memperlihatkan wajah lain: kota yang terburu-buru. Di bawah cahaya pagi yang tenang, manusia justru bergerak dengan gelisah, seakan lupa bahwa jalan adalah ruang bersama yang menuntut kesabaran dan saling menjaga.
Rossi, Waktu yang Disakralkan, dan Etika yang Menyingkir
Di ruang jalan yang padat itu, terjadi perubahan peran yang hampir serempak. Warga kota yang di ruang lain santun dan bersahabat, di balik setang dan kemudi menjelma menjadi pengendara agresif. Mendahului terasa lebih penting daripada mengalah, tiba lebih cepat terasa lebih utama daripada sampai ditujuan dengan selamat.
Metafora budaya populer menjadi relevan. Kita seperti seorang Valentino Rossi, dengan meniru semangatnya; cepat, kompetitif dan pantang kalah. Bedanya, ini bukan sirkuit. Tidak ada lintasan khusus, tidak ada pengawas, dan tidak ada ruang aman bagi kesalahan kecil. Yang ada hanyalah jalan umum, tempat berbagai kepentingan bertemu dan saling beririsan.
Dorongan utama dari perilaku ini hampir selalu sama: takut terlambat. Jam masuk kerja dan sekolah ditetapkan seragam, sementara jarak tempuh dan kondisi jalan yang relatif sempit tidak selalu bersahabat. Dalam situasi seperti ini, waktu menjadi nilai yang disakralkan. Ketepatan jam dipuja sebagai ukuran tanggung jawab, sementara cara mencapai ketepatan itu jarang dipersoalkan.
Lampu merah terasa sebagai rintangan, marka jalan diperlakukan sebagai formalitas, dan etika berlalu lintas perlahan menyingkir. Kita menjadi disiplin pada jam, tetapi longgar pada keselamatan. Seolah-olah tujuan yang baik dapat membenarkan cara yang berbahaya, padahal cara adalah bagian dari tujuan itu sendiri. Di titik ini, etika mulai tersisih oleh ambisi untuk tiba lebih dulu.
Normalisasi Risiko dan Lunturya Rasa Menjaga
Yang lebih mengkhawatirkan bukan hanya potensi kecelakaan, melainkan mekanisme normalisasi sosial. Ketika perilaku berisiko dilakukan secara massal dan berulang, ia tidak lagi dipersepsi sebagai pelanggaran. Narasi “semua orang juga begitu” kemudian berfungsi sebagai legitimasi moral yang menenangkan diri.
Jalan raya pun berubah menjadi ruang latihan intoleransi sehari-hari, kekerasan kecil yang terus diulang hingga kehilangan rasa bersalah. Ironisnya, di ruang lain kita terbiasa menjaga adab, menahan lisan, dan menghormati sesama. Namun di jalan raya, nilai-nilai itu kerap tertinggal, digantikan oleh dorongan untuk segera tiba, meski harus mengorbankan rasa aman orang lain.
Di titik ini, persoalan lalu lintas pagi hari tidak lagi sekadar urusan teknis berkendara, melainkan soal tanggung jawab moral: sejauh mana kita bersedia menahan diri demi keselamatan bersama.
Struktur Kota, Transportasi Publik, dan Amanah Kebijakan
Fenomena “pagi hari kita pembalap” tidak adil jika seluruh persoalan dibebankan sepenuhnya pada individu. Ia lahir dari struktur kota dan kebijakan yang membentuk pilihan-pilihan kita. Jam aktivitas yang berimpit, pemusatan fungsi kota, serta keterbatasan alternatif transportasi yang benar-benar sesuai kebutuhan warga, semuanya bertemu di jalan pada waktu yang sama.
Palu patut diapresiasi karena memiliki ikhtiar menghadirkan transportasi publik melalui ”Bus Trans Palu”. Namun pengalaman kota ini juga menunjukkan persoalan klasik kebijakan perkotaan yaitu keberlanjutan. Layanan ini pernah beroperasi, kemudian terhenti, dan dalam beberapa waktu terakhir kembali dijalankan. Bagi warga, situasi semacam ini menumbuhkan kehati-hatian, bukan pada niat, melainkan pada kepastian.
Transportasi publik bukan sekedar moda, juga tidak hanya soal ada atau tidak ada, melainkan amanah pelayanan. Ia soal konsistensi, keterandalan, dan kesesuaian rute dengan tujuan nyata warga. Ketika layanan hadir secara terputus-putus dan rutenya belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan harian, masyarakat cenderung menggunakan atau kembali ke kendaraan pribadi. Bukan karena abai, melainkan karena rasional. Dalam kondisi ini, jalan raya kembali menjadi arena kompetisi. Di sinilah kebijakan bertemu dengan kemaslahatan.
Disiplin yang Utuh dan Jalan Tengah Solusi
Di sinilah tampak bahwa persoalan lalu lintas pagi hari bukan sekadar masalah perilaku, melainkan cerminan dari disiplin yang belum utuh. Kita sangat ketat pada jam, tetapi longgar pada keselamatan. Padahal, dalam kehidupan bersama, cara sama pentingnya dengan tujuan; menahan diri adalah bagian dari tanggung jawab.
Solusi tentu tidak sederhana, tetapi juga bukan mustahil. Pertama, perlu keberanian menata ulang waktu aktivitas, jam kerja dan sekolah yang lebih fleksibel, setidaknya di wilayah perkotaan. Tidak semua harus dimulai di jam yang sama.
Kedua, optimalisasi transportasi publik seperti Bus Trans Palu harus berbasis kebutuhan riil warga: penyesuaian rute, integrasi, dan kepastian layanan. Transportasi publik yang relevan akan mengurangi tekanan di jalan raya.
Ketiga, pendidikan berlalu lintas perlu ditempatkan sebagai pendidikan etika sosial yakni tentang empati, kesabaran, dan kesediaan memberi ruang bagi orang lain.
Jalan adalah ruang aman bersama, dan keselamatan adalah hak setiap orang, menahan diri bukan tanda kalah. Dalam ruang bersama, justru di situlah letak kemenangan.
Menang dengan Menjaga
Pagi di Palu dimulai dengan cahaya yang tenang dari balik bukit, membuka Teluk Palu dengan lembut. Akan ironis jika ketenangan alam itu selalu kita balas dengan kegaduhan di jalan raya. Alam tidak pernah tergesa, tetapi selalu sampai pada waktunya.
Jalan bukan sirkuit. Kita bukan pembalap. Tidak ada podium bagi siapa pun yang tiba lebih dulu dengan mengorbankan rasa aman orang lain. Dalam hidup bersama, kemenangan sejati bukan soal kecepatan, melainkan menjaga; menjaga diri, menjaga sesama, dan menjaga kemaslahatan yang harus dirawat dengan adab.
Jika setiap pagi kita merasa harus menjadi Rossi, barangkali yang perlu diperlambat bukan laju kendaraan, tetapi juga kegelisahan dalam diri dengan cara kita mengatur waktu, Sebab kota yang baik bukan dibangun oleh kecepatan, melainkan oleh kesadaran dalam hidup bersama***.
Tentang Penulis; Penulis merupakan Akademisi dan Penulis Refleksi Sosial Kemasyarakatan Palu