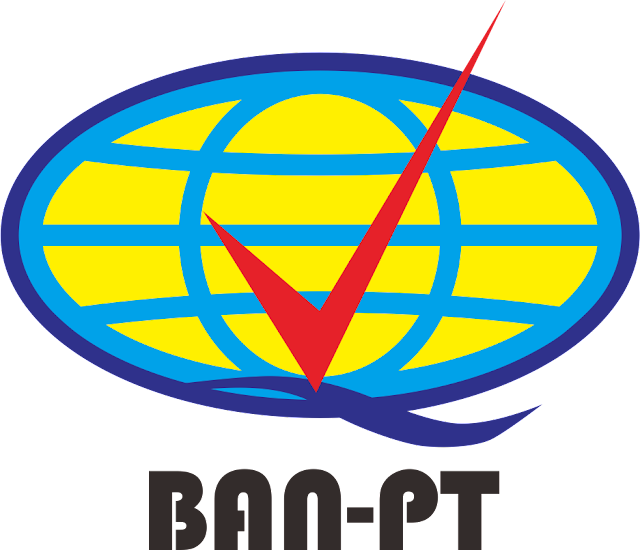Prof. Dr. H. Saepudin Mashuri, S.Ag., M.Pd.I
Guru Besar Bidang PAI Interdisipliner, FTIK UIN Datokarama PaluArtikel opini ini ingin memotret fakta yang selalu hadir di hadapan kita, insan akademik yang setiap hari bergelut dengan irama dan dialog intelektualitas. Kita selalu menyaksikan di ruang kelas, auditorium dan koridor kampus Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK), suara perdebatan ilmiah menggema hampir setiap hari. Mahasiswa sangat fasih membedah epistemologi hukum, hermeneutika teks agama, historisitas peradaban hingga dialektika filsafat-kalam yang rumit
Mereka mampu mengutip pemikir besar dunia dalam sekali napas intelektual. Namun, mengapa di balik kegemilangan intelektualitas tersebut, tersimpan sebuah ironi, spiritualitas yang kering-terabaikan. Seharusnya, semakin tinggi capaian intelektual-akademik, akan berbanding lurus dengan kematangan spiritual dan etika sosial kemanusiaan. Kita menyaksikan fenomena mahasiswa, di tengah kemajuan teknologi yang menawarkan konektivitas tanpa batas, namun justru menjebak mereka dalam “kemiskinan kontemplasi spritual”.
Azra (2012) menyoroti bahwa modernisasi pendidikan Islam menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara tradisi intelektual dan kedalaman spiritual. Kita menyaksikan lahirnya “intelektualisme kering”, bahkan pengabaian sengaja, tanpa praksis spritual bagi keutuhan manusia di hadapan Allah Swt. Agama dipelajari sebagai objek ilmu yang dingin di atas ruang kuliah, meja laboratorium dan forum seminar. Masalah ini diperparah oleh orientasi institusi yang terlalu mendewakan kuantitas kognitif-teoritik. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan kecepatan kelulusan sebagai standar utama yang dikejar secara berlebihan.
Kondisi ini sejalan dengan kekhawatiran Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah-nya, yang menyatakan bahwa pendidikan yang terlalu menekankan pada formalitas tanpa internalisasi nilai akan merusak daya kritis dan karakter asli manusia (Khaldun, 2001). Akibatnya, ruang-ruang kontemplasi, tadabur, muzdakarah dan pengabdian sosial yang tulus bagi kemanusiaan universal semakin menyempit. Diskursus spiritualitas tidak lagi menjadi “ruh” yang menggerakkan aksi kemanusiaan lintas batas pada medan kehidupan, melainkan hanya komoditas diskusi yang berhenti di ruang kuliah dan forum seminar. Inilah titik awal lahirnya karakter mahasiswa berkaca; ketika kecerdasan otak tidak lagi berdialog dengan spritualitas dan kelembutan hati.
Paradoks Koneksi dan Kerapuhan Jiwa
Kita membayangkan seorang mahasiswa duduk di kafe kampus keagamaan yang bising. Masing-masing matanya terpaku pada layar ponsel. Diantara mereka, ada yang mengunggah foto dengan kutipan tentang rasa syukur dan sabar yang puitis. Namun, di saat yang sama, hatinya justru dirongrong rasa cemas dan iri pada prestasi teman yang lain. Ia membandingkan hidupnya dengan pencapaian teman sebayanya di media sosial. Inilah gambaran paradoks spiritualitas mahasiswa milenial. Mereka fasih membicarakan Tuhan di ruang publik, namun sering kali merasa hampa saat sendirian menghadapi masalah hidup.
Sebagai generasi yang paling terhubung dalam sejarah manusia modern, mahasiswa milenial memiliki akses informasi yang tak terbatas. Namun, di tengah riuhnya notifikasi digital, mereka kehilangan koneksi yang paling krusial, yaitu koneksi antara diri sendiri dan Allah Swt, Sang Pencipta. Mahasiswa kaya akan koneksi digital, namun menderita dan mengalami kemiskinan kontemplasi spiritual yang akut. Kerapuhan ini bermula dari budaya serba instan yang mendewakan kecepatan teknologi digital sebagai sumber belajar agama. Erich Fromm (2013) menyebut fenomena ini sebagai kecenderungan “memiliki” (to have) daripada “menjadi” (to be). Mahasiswa lebih sibuk “memiliki” citra spiritual di ruang digital daripada benar-benar “menjadi” insan yang mengalami proses spiritual dalam kehidupan nyata.
Padahal, spiritualitas pada hakikatnya adalah sebuah proses yang berkembang “lambat”, dijalani dengan penuh rasa syukur, sabar dan tawakal, tidak bisa instan. Proses ini membutuhkan keheningan dan waktu yang panjang untuk mengakar kuat dalam dasar batin setiap manusia. Nasr (1993) berpendapat bahwa manusia modern cenderung kehilangan dimensi esoteris (batin) karena terlalu fokus pada aspek eksoteris (lahiriah). Kita sibuk dengan ritual yang tampak, tapi lupa pada hakikat yang tersimpan di dalamnya. Tidak heran, jika banyak manusia yang rajin beribadah, tetapi hati dan prilaku sosialnya mudah menyakiti orang lain. Manusia terjebak dalam ritualitas ibadah yang tidak berdampak pada harmoni kehidupan sosial kemanusiaan kita. Fenomena ini terlihat juga pada spiritualitas mahasiswa, mereka tidak memiliki fondasi yang mengakar kuat di dalam batin, mudah rapuh oleh validasi eksternal (kata, narasi, perbuatan dan prestasi) orang lain. Kondisi batin seperti ini menjadi indah di permukaan, namun mudah hancur saat diterjang badai kegagalan atau kritik kecil dalam interaksi sosial kehidupan.
Diskoneksi Teori dan Praksis di Lingkungan Akademik
Fenomena diskoneksi ini menjadi semakin ironis jika kita menilik dinamika kehidupan beragama di lingkungan PTK. Mahasiswa setiap hari bernapas dalam kultur akademik yang penuh dengan kajian teks suci keagamaan. Namun, sering kali terjadi jurang pemisah yang lebar antara kedalaman kajian agama dengan praksis kehidupan nyata. Kondisi ini mengingatkan kita pada kritik tajam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengenai “ulama su'” atau ilmuwan yang ilmunya tidak membuahkan amal. Al-Ghazali menegaskan bahwa ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan (Al-Ghazali, 2003).
Begitu pula Madjid (1997) menekankan bahwa tradisi Islam harus berfungsi secara transformatif dalam membangun karakter manusia, terutama mahasiswa sebagai estafet bangsa di masa depan. Tanpa internalisasi nilai-nilai spritual, mahasiswa hanya akan memiliki “daun” prestasi yang rimbun namun “akar” jiwanya tidak menghujam ke dalam bumi. Mereka memiliki kecerdasan kognitif yang memukau, segudang rekognisi prestasi dan IPK tertinggi, namun kehilangan daya juang (grit) karena spiritualitas yang tidak memberikan ketahanan batin. Krisis ini menciptakan apa yang disebut oleh Viktor Frankl sebagai “vakum eksistensial”, di mana seseorang memiliki segalanya untuk hidup (gelar, koneksi, fasilitas), namun tidak memiliki makna untuk apa ia hidup. Manusia kosong dari kebermaknaan hidup bagi sesama dan alam semesta (Frankl, 2017).
Kekosongan praktik ini melahirkan karakter spritual yang inkonsisten. Agama hanya dijadikan media untuk memenangkan perdebatan intelektual, bukan untuk memperbaiki kualitas diri yang terdalam, yaitu dimensi batin sebagai fondasi katahanan hidup manusia. Ketika spiritualitas hanya berhenti di tenggorokan, ia gagal menjadi kompas moral dalam kehidupan sosial-kemanusiaan mahasiswa. Dampaknya sangat nyata pada kemerosotan moral dan etika kemanusiaan universal; mudah iri, dengki, intoleransi, anarkis dan terpolarisasi karena sentimen etnosentris. Ilmu agama yang seharusnya melahirkan kasih sayang, justru sering melahirkan eksklusivitas intelektual yang sombong. Mahasiswa mudah terjebak pada merasa paling tahu tentang Tuhan, namun gagal melihat “wajah” Tuhan pada sesama yang menderita dan yang berbeda dengan dirinya pada medan kehidupan sosial di depan mata.
Krisis Spiritualitas Vertikal dan Horizontal
Kerapuhan spritual mencakup dua dimensi sekaligus, yaitu vertikal dan horizontal. Secara vertikal, hubungan dengan Tuhan sering kali bersifat transaksional, sekedar memenuhi kewajiban beragama. Ibadah dilakukan hanya untuk menggugurkan kewajiban akademik, mentaati aturan kampus atau mencari ketenangan sesaat agar lancar studinya. Tidak ada lagi proses muhasabah atau refleksi diri yang mendalam tentang tujuan hidup yang lebih besar sebagai praktik amal dari intelektualitas-keilmuawan yang diperoleh selama menjadi mahasiswa. Tuhan seolah hanya hadir di atas sajadah dan masjid semata, tapi absen di ruang kelas, laboratorium, forum seminar dan kegiatan organisasi kemahasiswaan.
Secara horizontal, pengabaian dimensi spiritual pasti berimbas pada tumpulnya kepekaan dalam kehidupan sosial, apalagi kolaborasi kemanusiaan lintas agama dan budaya. Mahasiswa milenial yang miskin kontemplasi spiritual cenderung terjebak dalam narsisme akademik. Orientasi hidup mereka adalah bagaimana membangun portofolio yang mengesankan bagi dunia kampus dan rekognisi akademik, bukan memberi dampak nyata bagi harmoni kemanusiaan dan alam semesta. Padahal, spiritualitas yang sehat seharusnya berbuah pada akhlak sosial yang mulia sesuai pesan Islam sebagai agama Rahmatal lil ‘alamin. Syukur (2012) menjelaskan bahwa tasawuf kontekstual seharusnya menjadi solusi bagi problem manusia modern, termasuk dalam mengatasi individualisme yang akut di era keterbukaan informasi dan kolaborasi hari ini. Ilmu yang tinggi seharusnya melahirkan tanggung jawab sosial yang besar, bukan keterasingan diri dari realitas sosial-kamanusiaan universal masyarakat multikultural yang semakin menggelobal.
Kesimpulan
Sebagai simpulan, kerapuhan karakter spiritual pada mahasiswa milenial berakar pada pengabaian terhadap dimensi kontemplatif dan pengagungan berlebih terhadap aspek intelektual-formal. Sistem pendidikan yang hanya mengejar angka-angka administratif akan gagal melahirkan manusia yang tangguh secara mental-spritual. Untuk membenahi hal ini, penguatan kembali budaya kontemplasi dan integrasi aspek batin dalam pendidikan keagamaan menjadi kebutuhan mendesak di era digital yang serba instan.
Mahasiswa perlu didorong untuk kembali menemukan “ruang sunyi” di tengah kebisingan algoritma angka-angka digital. Hamka (2015) menegaskan bahwa ketenangan jiwa berasal dari kemampuan batin untuk senantiasa terhubung dengan Tuhan dalam setiap keadaan. Kontemplasi bukan tindakan pelarian, melainkan upaya menyatukan kembali kecerdasan logika dengan kematangan spiritual. Dengan menyelaraskan koneksi luar dan kontemplasi dalam, akan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kokoh secara karakter dan penuh cinta pada kemanusiaan universal.