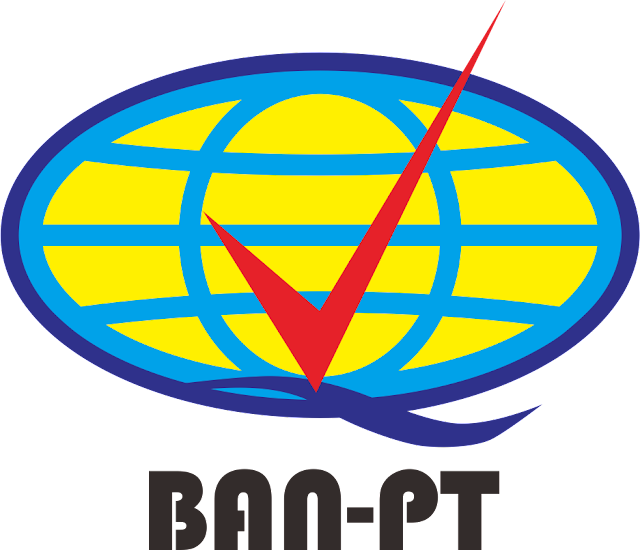Penulis: Randy Atma R Massi, Dosen Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu
Rentetan bencana alam yang melanda Indonesia sepanjang 2025 kembali mengingatkan kita pada kerapuhan sistem penanggulangan bencana di negeri ini. Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera akhir November 2025 mencatat angka yang sangat memilukan ratusan nyawa melayang dan ratusan lainnya dinyatakan hilang.
Kejadian ini, menyusul sederet bencana serupa di berbagai wilayah Indonesia, memperlihatkan betapa kita masih bergerak dalam lingkaran tanggap darurat tanpa pernah benar-benar keluar menuju sistem mitigasi dan pencegahan yang kokoh.
Ironi ini semakin terlihat ketika kita melihat tren bencana yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Data historis BNPB tahun 2017 yang pernah saya analisis dalam penelitian terdahulu mencatat 2.341 kejadian bencana dengan 377 jiwa meninggal, 3,5 juta jiwa menderita dan mengungsi, serta 47 ribu unit rumah rusak. Kini di tahun 2025, angka-angka tersebut melonjak drastis. Angka-angka ini bukan sekadar statistik ia adalah cermin kegagalan kita mentransformasi pengalaman pahit menjadi kebijakan konkret di tingkat daerah.
Hukum yang Tidak Menyentuh Bumi
Problem mendasar penanggulangan bencana Indonesia terletak pada jurang antara regulasi nasional dan implementasi daerah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang telah diperbarui dengan UU Nomor 6 Tahun 2024 mengamanatkan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab penuh penyelenggaraan penanggulangan bencana. Regulasi terbaru ini semakin menegaskan pentingnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam kerangka penanggulangan bencana. Namun, amanat ini seringkali tersesat dalam birokrasi karena ketiadaan payung hukum lokal yang operasional.
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Bencana seharusnya menjadi wujud konkret hukum yang “benar-benar bersentuhan dengan masyarakat secara langsung,” sebagaimana hakikat Perda dalam hierarki perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kenyataannya, banyak daerah masih mengandalkan regulasi nasional yang sifatnya umum, tanpa menerjemahkannya ke dalam konteks geografis, geologis, dan sosiologis wilayahnya masing-masing.
Ketika bencana menerjang Sumatera hari ini, pertanyaan mendasar bukan hanya tentang kecepatan tanggap darurat, melainkan apakah daerah tersebut memiliki Perda Kebencanaan yang mengatur pemetaan risiko, jalur evakuasi, protokol koordinasi lintas sektor, hingga mekanisme pemulihan pasca-bencana? Ketiadaan regulasi lokal ini membuat setiap bencana seolah menjadi “kejutan” yang harus direspons secara improvisatif.
Krisis Lingkungan sebagai Akar Persoalan
Al-Quran dalam Surat Ar-Rum ayat 41 telah mengingatkan: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.” Ayat ini bukan sekadar peringatan teologis, melainkan diagnosis akurat atas krisis lingkungan kontemporer yang memperparah kerentanan bencana sebuah tema yang telah saya teliti pada Tahun 2019 dalam konteks urgensi regulasi daerah untuk penanggulangan bencana.
Paradigma antroposentris dalam pembangunan modern telah mendorong eksploitasi alam melampaui batas. Riset Yayasan Auriga sebagaimana dilaporkan Mongabay mengungkap fakta mengejutkan: dalam kurun waktu delapan tahun (2016-2024), sekitar 1,4 juta hektare hutan telah hilang di tiga provinsi Sumatera yang kini dilanda bencana. Deforestasi masif untuk perkebunan dan pertambangan, alih fungsi lahan tanpa kajian daya dukung lingkungan, hingga pembangunan infrastruktur yang mengabaikan aspek mitigasi bencana semuanya bermuara pada satu fakta kita sedang menggali lubang bencana dengan tangan kita sendiri.
Data Wikipedia menunjukkan bahwa di Sumatera terdapat 1.907 wilayah izin usaha pertambangan aktif dengan luas mencapai 2.458.469,09 hektare setara dengan empat kali luas Brunei Darussalam. Bayangkan, hampir seperempat juta hektare lahan telah dikonversi menjadi kawasan tambang yang mengubah fungsi hidrologis wilayah secara drastis. Bencana hidrometeorologi banjir, tanah longsor, dan puting beliung yang mendominasi kejadian bencana di Indonesia bukanlah semata-mata takdir alam, melainkan konsekuensi logis dari kerusakan lingkungan sistematis yang dibiarkan berlangsung tanpa kontrol hukum yang memadai di tingkat lokal.
Sulawesi Tengah: Cermin Bencana yang Akan Datang
Provinsi Sulawesi Tengah harus mengambil pelajaran penting dari tragedi Sumatera. Sebagai salah satu pusat pertambangan nikel terbesar di Indonesia, Sulteng berada pada titik kritis yang sama. Laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah mengungkap kondisi yang sangat mengkhawatirkan: terdapat 125 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi nikel dengan luas konsesi mencapai 500.000 hektar atau 12,5% dari total daratan Sulawesi Tengah. Angka ini bukan main-main seperdelapan dari total wilayah provinsi telah berubah menjadi kawasan pertambangan.
Situasi di Kabupaten Morowali bahkan lebih kritis. Data JATAM Sulteng menunjukkan terdapat 53 IUP operasi produksi dengan total luas konsesi 118.139 hektare yang beroperasi di kawasan pegunungan zona yang seharusnya menjadi daerah resapan air dan penyangga ekosistem. Dampaknya sudah mulai terasa nyata. Liputan Mongabay Indonesia pada pertengahan Maret 2025 melaporkan banjir bandang menerjang kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, dengan empat pekerja tertimbun longsoran. Ini bukan kejadian pertama banjir lumpur telah menjadi langganan tahunan di Desa Labota dan sekitarnya, sebuah pola yang mengingatkan kita pada awal mula bencana Sumatera.
Kajian Yayasan Trend Asia (YTA) sebagaimana dimuat dalam berbagai publikasi lingkungan mengungkap fakta yang lebih mengkhawatirkan: deforestasi akibat pertambangan nikel di Indonesia telah mencapai 86.000 hektar, dengan pembukaan lahan yang bahkan mencaplok daerah hutan lindung dan kawasan yang seharusnya dijaga untuk kelestarian lingkungan. Ironisnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan meski Sulawesi Tengah memiliki 22% cadangan nikel nasional, angka kemiskinan di provinsi ini masih berada di level 11,77% pada semester pertama 2024 lebih tinggi dari rata-rata nasional. Ini adalah paradoks klasik: kaya sumber daya alam, tetapi masyarakatnya tetap miskin, sementara ancaman bencana semakin nyata.
Yang lebih memprihatinkan lagi, penelitian valuasi ekonomi oleh Yayasan Trend Asia menunjukkan bahwa 35% wilayah Morowali atau 157.935 hektare telah dikonversi menjadi konsesi tambang nikel untuk 70 perusahaan. Dari luasan tersebut, 97.790 hektare berada di hutan primer yang seharusnya dilindungi. Studi yang sama menemukan bahwa nilai ekonomi hutan Morowali yang utuh bisa mencapai Rp 2,81 triliun per tahun angka yang lebih tinggi dari pendapatan daerah. Temuan ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan serius: kita sedang mengorbankan aset jangka panjang demi keuntungan jangka pendek yang bahkan tidak dirasakan sebagian besar masyarakat.
Sulawesi Tengah tidak boleh mengulangi kesalahan Sumatera. Pengelolaan pertambangan yang buruk di Sumatera telah mengubah berkah sumber daya alam menjadi kutukan ekologis. Sulteng harus segera mengambil langkah proaktif dengan menetapkan Perda Kebencanaan yang secara khusus mengatur: Pertama, moratorium izin tambang baru di kawasan hulu DAS dan hutan primer. Kedua, evaluasi menyeluruh terhadap 125 IUP yang telah terbit dengan mekanisme audit lingkungan yang ketat. Ketiga, penetapan zona terlarang pertambangan di kawasan rawan bencana berdasarkan kajian risiko yang komprehensif. Keempat, kewajiban restorasi dan reklamasi lahan bekas tambang dengan sanksi pidana dan pencabutan izin bagi pelanggar.
Perda sebagai Instrumen Rekayasa Sosial
Dalam penelitian saya tahun 2019 yang dipublikasikan di Jurnal Bilancia tentang urgensi Perda dalam penanggulangan bencana, saya telah menekankan bahwa Perda bukan sekadar instrumen administratif, melainkan alat rekayasa sosial (social engineering) untuk mengubah perilaku eksploitatif menjadi kultur mitigasi dan resiliensi. Kini, dengan ancaman perubahan iklim yang semakin nyata dan tekanan industri ekstraktif yang semakin massif sebagaimana ditunjukkan oleh data-data JATAM Sulteng dan Trend Asia argumen ini menjadi semakin relevan dan mendesak.
Perda yang ideal harus mengintegrasikan empat dimensi Pertama, dimensi preventif melalui pengaturan tata ruang berbasis risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, pembatasan kegiatan ekonomi di zona rawan, sanksi tegas bagi aktivitas pertambangan ilegal, dan insentif bagi praktik ramah lingkungan. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2024, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan kawasan terlarang bagi aktivitas yang meningkatkan risiko bencana.
Kedua, dimensi responsif dengan protokol tanggap darurat yang jelas, sistem peringatan dini berbasis teknologi, mekanisme koordinasi multi-stakeholder yang efektif, dan kesiapan logistik serta hunian sementara. Pengalaman bencana Palu 2018 yang telah kita dokumentasikan dalam ingatan telah mengajarkan kita pentingnya kesiapsiagaan ini.
Ketiga, dimensi restoratif melalui skema pemulihan ekonomi korban, rehabilitasi infrastruktur berkelanjutan, program trauma healing, dan mekanisme kompensasi dari perusahaan tambang yang terbukti memperparah risiko bencana. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah telah memberikan kerangka pendanaan yang memadai untuk dimensi ini.
Keempat, dimensi partisipatif yang melibatkan masyarakat, akademisi, dan sektor swasta dalam penyusunan hingga evaluasi kebijakan kebencanaan sesuai dengan prinsip pembentukan Perda yang baik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2022.
Yang tidak kalah penting, Perda harus memuat sanksi tegas bagi pelaku kerusakan lingkungan yang meningkatkan risiko bencana. Laporan media nasional mencatat Satgas Pemberantasan Kegiatan Pertambangan Ilegal (PKH) telah menindak pertambangan nikel ilegal di Morowali dengan potensi denda mencapai Rp 2,3 triliun. Namun, tanpa Perda yang kuat sebagai payung hukum lokal, penegakan hukum akan tetap sporadis dan tidak sistematis. Perda memberikan kepastian hukum bagi aparat dalam menindak pelanggaran dan sekaligus efek jera bagi pelaku.
Sinergi Regulasi: Dari Pusat hingga Desa
Kerangka hukum penanggulangan bencana saat ini sebenarnya sudah cukup komprehensif. Selain UU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Bencana yang menyempurnakan UU Nomor 24 Tahun 2007, terdapat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengatur skema pendanaan penanggulangan bencana dengan lebih jelas. Ditambah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang juga menyentuh aspek tata ruang dan lingkungan hidup dalam konteks pembangunan berkelanjutan.
Namun, kompleksitas regulasi ini justru memerlukan Perda sebagai “penerjemah” yang membumikan amanat undang-undang ke dalam realitas lokal. Sebagaimana saya argumentasikan dalam penelitian 2019 di Jurnal Bilancia, Perda yang baik harus mampu menjembatani regulasi nasional dengan kearifan lokal, antara standar pelayanan minimum nasional dengan keunikan karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi daerah. Perda Sulteng tentang kebencanaan, misalnya, harus secara spesifik mengatur bagaimana mengelola risiko bencana di kawasan pertambangan nikel—sesuatu yang tidak akan ditemukan secara detail dalam regulasi nasional yang bersifat umum. Data JATAM Sulteng tentang 125 IUP dan temuan Trend Asia tentang deforestasi harus menjadi basis empiris penyusunan Perda tersebut.
Dari Tanggap Darurat Menuju Budaya Siaga
Perubahan paradigma dari reaktif ke proaktif memerlukan political will pemerintah daerah untuk menempatkan Perda Kebencanaan sebagai prioritas legislasi. Sayangnya, proses pembentukan Perda kerap terhambat oleh kepentingan politik jangka pendek yang tidak melihat penanggulangan bencana sebagai investasi strategis. Padahal, kerugian ekonomi akibat bencana sebagaimana ditunjukkan oleh kasus Sumatera 2025 jauh lebih besar daripada biaya pencegahan.
Dengan dasar yuridis yang jelas mulai dari Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang memberikan kewenangan daerah untuk menetapkan Perda, UU Nomor 6 Tahun 2024 yang mengamanatkan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab penanggulangan bencana, hingga UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menjamin ketersediaan dana tidak ada alasan bagi daerah untuk menunda pembentukan Perda ini. Apalagi ketika kita mengingat bahwa Indonesia adalah negara kedua paling rentan bencana di dunia.
Perda yang disusun dengan landasan filosofis (perlindungan segenap warga dari ancaman bencana dan dampak perubahan iklim serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali), landasan sosiologis (nilai-nilai kearifan lokal dalam menghadapi bencana dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan), dan landasan yuridis (kewenangan daerah berdasarkan regulasi terkini), akan menjadi instrumen yang legitimate dan efektif sebuah prinsip yang telah saya uraikan dalam kajian 2019 dan kini semakin mendesak untuk diimplementasikan mengingat data-data terkini dari JATAM, Trend Asia, dan berbagai lembaga pemantau lingkungan.
Penutup: Jangan Tunggu Bencana Berikutnya
Bencana yang melanda Sumatera dan berbagai wilayah Indonesia tahun ini seharusnya menjadi momentum refleksi kolektif. Kita tidak bisa lagi mengandalkan pola lama: bencana datang, bantuan mengalir, media meliput, lalu semuanya terlupakan hingga bencana berikutnya datang.
Khusus untuk Sulawesi Tengah, peringatan ini harus didengar dengan sungguh-sungguh. Berdasarkan data JATAM Sulteng, dengan 125 IUP nikel yang beroperasi dan terus bertambah, dengan deforestasi yang terus meluas mencapai puluhan ribu hektare sebagaimana dicatat Trend Asia, dengan banjir lumpur yang sudah menjadi rutinitas tahunan di kawasan pertambangan sebagaimana dilaporkan Mongabay Sulteng sedang berjalan di jalur yang sama dengan Sumatera. Perbedaannya hanya soal waktu. Data-data yang saya paparkan dari berbagai sumber kredibel ini bukan sekadar angka statistik, melainkan alarm bahaya yang harus segera ditanggapi dengan tindakan konkret.
Sudah saatnya setiap daerah di Indonesia, terutama Sulawesi Tengah, memiliki Perda Penanggulangan Bencana yang tidak hanya memenuhi formalitas hukum, tetapi benar-benar berfungsi sebagai sistem perlindungan masyarakat yang komprehensif dan responsif terhadap ancaman perubahan iklim serta dampak eksploitasi sumber daya alam. Hukum harus hadir bukan sekadar “di atas kertas,” melainkan dalam wujud yang memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat yang hidup di wilayah rawan bencana—sebuah prinsip yang sejak awal telah saya tekankan dalam penelitian tentang urgensi Perda kebencanaan yang dipublikasikan di Jurnal Bilancia tahun 2019.
Ayat Al-Quran yang saya kutip di awal tulisan diakhiri dengan ajakan: “agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” Kembali ke jalan yang benar dalam konteks kebencanaan berarti kembali pada keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, antara ambisi ekonomi dan tanggung jawab ekologis, antara eksploitasi dan konservasi. Ini bukan romantisme lingkungan, melainkan perhitungan ekonomi rasional berdasarkan studi Trend Asia: nilai ekonomi hutan Morowali yang utuh (Rp 2,81 triliun per tahun) lebih tinggi dari keuntungan pertambangan jangka pendek.
Perda Kebencanaan adalah salah satu jalan kembali itu. Pertanyaannya: masih berapa banyak korban yang harus berjatuhan, berapa banyak hutan yang harus hilang, berapa banyak banjir yang harus terjadi sebelum kita benar-benar berjalan di jalan tersebut?
Sulawesi Tengah masih punya waktu untuk tidak mengulangi tragedi Sumatera. Tapi waktu itu tidak akan lama. Hujan deras berikutnya, banjir lumpur berikutnya, longsor berikutnya bisa jadi adalah peringatan terakhir sebelum bencana besar yang tidak bisa lagi kita tangani hanya dengan tanggap darurat. Saatnya bertindak adalah sekarang. Saatnya Perda Kebencanaan disahkan adalah hari ini bukan besok, bukan tahun depan, apalagi setelah bencana besar merenggut ribuan nyawa seperti yang terjadi di Sumatera.
Data dari JATAM Sulteng, Trend Asia, Mongabay, dan lembaga pemantau lingkungan lainnya telah memberikan peringatan yang cukup. Kini giliran para pemangku kebijakan di Sulawesi Tengah untuk bertindak. Masyarakat Sulteng, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil harus terus mendesak DPRD dan Gubernur untuk menjadikan Perda Kebencanaan sebagai prioritas legislasi 2025. Jangan biarkan data-data ini hanya menjadi arsip akademis. Jadikanlah ia sebagai landasan kebijakan yang menyelamatkan nyawa.****
Tentang Penulis:
Randy Atma R Massi, adalah akademisi hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu yang fokus pada kajian Legal Drafting, Pluralisme hukum dan Kearifan lokal dalam sistem hukum Indonesia. Opini ini merupakan pandangan pribadi penulis berdasarkan penelitia yang Pernah dipublikasikan di Jurnal Bilancia Vol. 13 No. 1 Januari-Juni 2019 dan pengamatan terhadap dinamika penanggulangan bencana di Indonesia dengan merujuk pada data-data terkini dari berbagai lembaga kredibel, dan tidak mewakili institusi tempat penulis mengabdi.