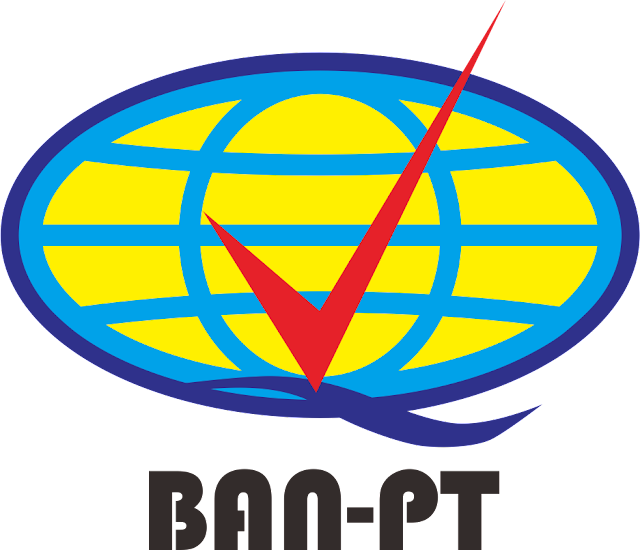Bagian Kedelapan dari Jejak-Jejak Safira dan Sang Guru
“Hati yang tidak dijaga akan mencari pelukan di luar rumah, padahal kehangatan sejati menunggu di dalam” ____ Lukman S. Thahir
Rumah Tangga: Perjalanan Menuju Kematangan Jiwa
Keluarga merupakan institusi pertama tempat manusia belajar makna kasih, tanggung jawab, dan maaf. Dalam perspektif psikologi Islam, hubungan suami istri bukan hanya kontrak sosial, melainkan juga ‘ibadah ruhaniyah — perjalanan menuju kematangan jiwa.
Ketika konflik hadir, Islam tidak mendorong penyangkalan, tetapi tazkiyah, penyucian diri melalui kesabaran dan kejujuran dalam komunikasi.
Dalam konteks ini, kisah “Retak yang Tak Terdengar” bukan sekadar cerita rumah tangga yang nyaris hancur, tetapi refleksi tentang bagaimana doa yang terabaikan bisa menjadi celah masuknya jarak — dan bagaimana keikhlasan mampu menjahit kembali luka yang pernah dibiarkan terbuka.
Kisah Inspiratif: Retak Tak Terdengar
Di ruang kantor yang sepi selepas jam kerja, lampu monitor memantulkan bayangan wajah lelah Firdaus. Di kursi seberang, Laila menatap layar yang sama. Percakapan awalnya ringan—tentang laporan dan tenggat waktu—namun setiap tawa kecil mereka menjadi langkah ke arah jurang yang tak mereka sadari.
Di rumah, istri Firdaus menyiapkan makan malam sambil menatap jam dinding. Ia tahu tubuh suaminya masih di kantor, tapi tak tahu bahwa hatinya mulai berjalan pulang lebih lambat. Hingga suatu malam, pesan yang salah terkirim menjadi badai yang menghantam rumah tangga mereka. Bukan hanya pesan singkat yang terbaca, tapi juga retak yang selama ini diam.
Firdaus menatap wajah istrinya yang basah air mata. Ia sadar, yang ia cari di luar bukan cinta baru—melainkan rasa dihargai yang tak pernah ia pinta. Dan malam itu, hatinya seperti disadarkan. Ia mengerti, bahwa kehilangan terbesar bukan saat seseorang pergi, tapi saat kita sendiri berhenti berjuang untuk mempertahankan yang pernah kita raih dengan doa-doa penuh ketulusan. Di luar, malam masih diam. Namun di dalam hati Firdaus, sesuatu mulai bicara –pelan, tapi jujur. Dan dari kejauhan, seolah ada Cahaya yang sedang menuntun pulang.
Beberapa minggu setelah badai di rumah mereka, Firdaus dan istrinya hidup dalam sunyi. Ia tetap berangkat ke kantor setiap pagi, tapi kini tanpa semangat. Suatu sore, seorang ibu tetangga mengetuk pintu. “Di balai RT malam ini ada pengajian kecil. Ada seorang guru yang bijaksana dan muridnya, katanya mereka diundang untuk berbicara tentang ‘menjaga hati di zaman bising’. Datanglah, Nak. Barangkali menenangkan.”
Dengan ragu, keduanya datang. Balai itu sederhana; tikar pandan terbentang, dan di depan duduk seorang guru bersorban putih dan murid perempuannya, Safira, yang ketika itu duduk membaur dengan masyarakat menikmati wejangan-wejangan sang guru yang sangat inspiratif. Di sela-sela tanya jawab yang sudah diagendakan oleh panitianya, Safira mengangkat tangannya dan membuka percakapan, dengan suaranya yang lembut tapi tajam. “Kadang bukan orang ketiga yang memecah rumah tangga, guru, tapi jarak yang kita biarkan tumbuh di antara doa-doa yang tak lagi kita ucapkan bersama.”
Sang Guru menimpali dengan senyum tenang, “Rumah tangga ibarat taman. Bila kita sibuk menyiram bunga orang lain, bunga di halaman sendiri akan layu. Padahal yang diminta Allah bukan taman yang sempurna, tetapi tangan yang setia merawat.”
Ruangan saat itu diam dan hening, Guru dengan senyumannya yang meneduhkan, berhenti sejenak lalu menatap hadirin dengan lembut, sambil berkata kepada Safira:
“Muridku, orang ketiga itu tidak datang membawa kehancuran; ia datang membawa cermin. Ia memperlihatkan bagian dari cinta yang tak lagi kita rawat.”
Safira terdiam, mendengar nasehat gurunya, dan dengan memberanikan dirinya, ia bertanya: Guru… bagaimana menjaga cinta agar tak retak?” “Dengan terus berbicara meski suaramu gemetar, dengan saling mendoakan meski sedang menjauh, dan dengan belajar mencintai bukan karena bahagia, tapi agar bahagia.”
Karena itu, Safira, termasuk semua yang hadir di sini, aku ingin kalian camkan baik-baik perkataanku: “Apabila tamanmu pernah layu, jangan malu untuk menanam Kembali. Cinta tidak menuntut masa lalu yang tanpa luka, tapi keberanian untuk memulai lagi dari tanah yang sama. Jangan biarkan gengsi lebih tinggi dari maaf, sebab di situlah pintu Rahmat Allah sering terbuka. Cinta yang pernah terluka, bila disirami kembali dengan maaf dan kesetiaan, segersang apa pun taman, pasti bisa tumbuh lagi”.
Kata-kata itu menembus dinding hati Firdaus dan istrinya. Mereka saling berpandangan, mata mereka basah, seolah untuk pertama kali kembali mengenal satu sama lain. Sepulang dari pengajian, Firdaus berhenti di depan rumah. Ia memegang tangan istrinya dan berbisik, “Maukah kamu memulai lagi memperbaiki taman kita, dari doa yang sama?” Dan malam itu, rumah mereka kembali bernyawa.
Renungan Penutup
Kebenaran tak selalu lahir dari argumen yang keras, sebab cahaya tak pernah berteriak hanya untuk membuktikan bahwa ia menerangi. Ada kalanya, dalam diam, hati belajar mendengar lebih dalam. Kadang, justru saat kita berhenti ingin menang, kebenaran itu muncul — lembut, tapi pasti. Seperti embun yang turun tanpa suara, namun menghidupkan seluruh taman.
Kesetiaan bukan tentang tidak pernah goyah, melainkan tentang selalu kembali pada niat awal: untuk menjaga, bukan menguasai; untuk menumbuhkan, bukan menghakimi. Dalam rumah tangga, ujian bukan tanda berakhirnya cinta, tapi panggilan untuk memperbaharui doa yang dulu pernah kita panjatkan bersama. Sebab cinta yang berakar pada Allah, akan menemukan jalannya meski telah tersesat di tengah badai _________ Lukman S. Thahir.